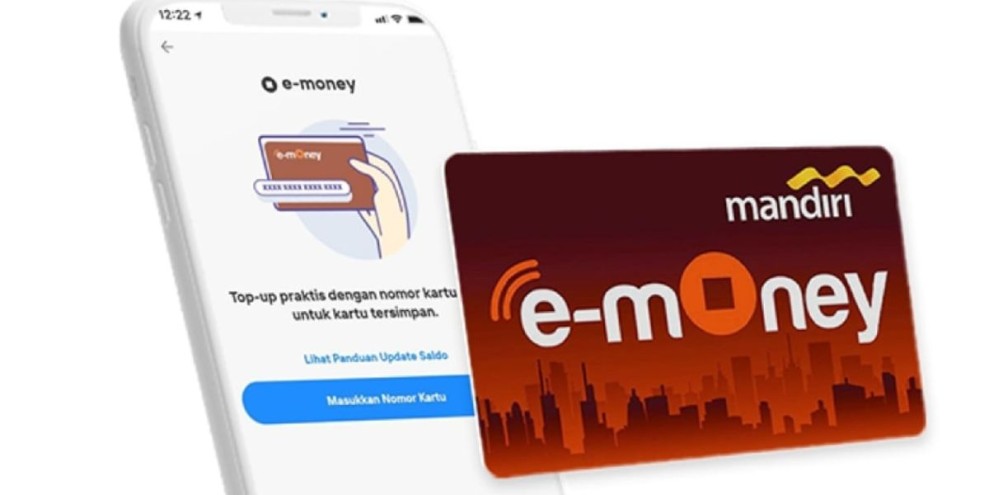Sejarah Tari Indang merupakan bagian penting dari kekayaan budaya yang berasal dari Pulau Sumatera, khususnya dari Provinsi Sumatera Barat.
Wilayah yang dikenal dengan ikon Jam Gadang ini tidak hanya memikat lewat wisata dan kulinernya, tetapi juga melalui ragam seni tradisional yang mencerminkan kehidupan masyarakat setempat.
Salah satu bentuk seni yang paling dikenal dari daerah ini adalah Tari Indang, yang berasal dari kawasan Pariaman dan merupakan warisan budaya suku Minangkabau.
Tarian ini telah berkembang menjadi salah satu kesenian tradisional yang dikenal luas di berbagai penjuru Indonesia.
Istilah "indang" berasal dari bahasa Minang, yang merujuk pada alat musik berupa rebana kecil. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan lain, yaitu Tari Dindin Badindin.
Dalam pelaksanaannya, gerakan Tari Indang memiliki kemiripan dengan Tari Saman dari Aceh, namun dengan tempo yang lebih tenang dan lambat.
Tari Indang lahir dari proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal Minangkabau. Awalnya, kesenian ini dibawa oleh para ulama dari Aceh ke Padang Pariaman sebagai media untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat.
Selain sebagai sarana dakwah, tarian ini juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual individu.
Nilai-nilai kejiwaan yang terkandung dalam syair lagu pengiring tarian dipercaya mampu membangkitkan semangat rohani, terutama dalam aspek keagamaan dan adat. Gerakan dalam tarian ini dikenal dinamis, lincah, dan penuh variasi.
Ciri khasnya terletak pada jentikan jari dan tepukan tangan yang menjadi elemen utama dalam pertunjukan.
Sebagai bentuk seni pertunjukan, Tari Indang tidak hanya menyampaikan pesan budaya dan sosial, tetapi juga menyiratkan nilai-nilai religius. Pertunjukan ini biasanya dilakukan di masjid atau surau oleh anak laki-laki berusia antara 7 hingga 15 tahun.
Seiring waktu, Tari Indang terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat luas. Di tanah asalnya, Pariaman, tarian ini tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya lokal.
Untuk memahami lebih dalam mengenai makna, gerakan, dan properti yang digunakan dalam pertunjukan ini, penelusuran terhadap sejarah Tari Indang menjadi langkah awal yang penting.
Sejarah Tari Indang
Sejarah Tari Indang berawal dari peran Syekh Burhanuddin yang memperkenalkan tarian ini sekitar abad ke-13 atau ke-14 sebagai bagian dari upaya penyebaran ajaran Islam di wilayah Sumatera Barat.
Dalam beberapa catatan lain, disebutkan bahwa tarian yang juga dikenal sebagai dindin badinding ini sebenarnya berasal dari para pedagang Arab yang singgah di Minangkabau.
Selain berdagang, mereka turut membawa misi dakwah melalui jalur perdagangan, yang kemudian menciptakan interaksi budaya antara masyarakat pesisir Minang dan para pendatang dari Timur Tengah.
Salah satu pengikut Syekh Burhanuddin bernama Rapa’i kemudian memperkenalkan tarian ini dalam perayaan Tabuik di Pariaman, sebuah tradisi masyarakat pesisir Sumatera Barat yang digelar untuk mengenang wafatnya Imam Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW.
Sejak saat itu, Tari Indang menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukan dalam festival Tabuik dan terus dipertahankan hingga kini.
Pada awalnya, pertunjukan tari ini diiringi oleh alat musik perkusi berupa rebana, yakni gendang bundar pipih yang terbuat dari kayu dengan bagian ujung yang melebar dan tinggi yang pendek.
Tarian ini juga dianggap sakral karena melibatkan kelompok sipatuang sirah—para tetua yang diyakini memiliki kekuatan spiritual dalam setiap kelompok penari.
Fungsi utama dari Tari Indang adalah sebagai sarana dakwah para ulama dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Selain itu, tarian ini memiliki aturan khusus dalam pelaksanaannya, yaitu indang naik dan indang turun.
Indang naik biasanya dipentaskan pada malam pertama sekitar pukul 11 hingga 12 malam, sedangkan indang turun ditampilkan menjelang malam setelah waktu Magrib. Namun, seiring waktu, aturan tersebut mulai ditinggalkan.
Tarian ini mencerminkan karakter masyarakat Padang Pariaman yang sederhana, penuh rasa hormat, dan taat kepada Tuhan.
Meski awalnya berfungsi sebagai media dakwah, kini Tari Indang juga dipentaskan sebagai hiburan, menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat modern.
Fungsi dan Makna Tari Indang
Setiap bentuk seni tradisional yang berasal dari suatu wilayah tentu memiliki maksud, peran, dan makna yang khas. Hal ini juga berlaku bagi tarian khas dari Padang Pariaman.
Walaupun bentuk dan penyajiannya telah mengalami berbagai penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman, esensi dari gerak dan pesan yang disampaikan tetap terjaga.
Meski tampak berbeda dari versi awalnya, inti dari tarian ini tetap menggambarkan proses masuknya ajaran Islam ke daerah Sumatera Barat. Hal tersebut terlihat jelas dalam lirik lagu pengiring serta gerakan para penarinya.
Bila diperhatikan secara menyeluruh dari awal hingga akhir pertunjukan, tampak bahwa para penari menyampaikan kisah tentang kebesaran ajaran Islam yang mereka yakini, termasuk narasi mengenai awal mula penyebarannya di wilayah Minangkabau.
Pada masa awal kemunculannya, tarian ini digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pendidikan dan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat.
Selain itu, ia berfungsi sebagai media dakwah yang menyampaikan pujian dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW melalui syair-syair yang bernuansa religius.
Kini, fungsi tarian tersebut telah berkembang menjadi hiburan yang ditampilkan dalam berbagai jenis acara. Mulai dari kegiatan keagamaan, upacara adat, hingga perhelatan resmi maupun santai.
Dalam konteks keagamaan, tarian ini sering dipentaskan dalam Festival Tabuik di Pariaman, yang merupakan peringatan atas wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 10 Muharram.
Di luar itu, tarian ini juga kerap digunakan untuk menyambut tamu, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Tak hanya terbatas pada acara keagamaan dan penyambutan, tarian ini juga hadir dalam berbagai perayaan lainnya.
Misalnya dalam pesta pernikahan, upacara adat, pengangkatan pemimpin adat, pertunjukan seni, dan berbagai kegiatan serupa lainnya.
Gerakan Tari Indang
Di awal pementasan tarian yang juga dikenal dengan sebutan dindin badinding, dua kelompok penari akan membentuk barisan sejajar dari sisi kiri menuju kanan panggung.
Setelah itu, mereka mulai melakukan berbagai variasi gerakan. Sebagian penari langsung duduk bersila, sementara yang lain terlebih dahulu menampilkan gerakan sambil berdiri sebelum akhirnya ikut duduk.
Ketika semua penari telah duduk bersila, masing-masing akan meletakkan alat musik indang di hadapan mereka. Selanjutnya, mereka memberi penghormatan dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada.
Begitu musik mulai ditabuh, penari mulai bergerak dan menciptakan bunyi, baik dari alat musik indang maupun dari tepukan tangan. Gerakan mereka disesuaikan dengan irama yang mengiringi.
Ragam gerakan dalam tarian ini cukup beragam. Penari akan meliukkan tubuh ke kanan dan kiri secara bergantian, lalu bergerak maju dan mundur dengan pola yang sama.
Variasi gerakan ini berlangsung dari awal hingga akhir pertunjukan, menciptakan dinamika yang khas. Setiap gerakan dalam tarian ini mengandung makna mendalam. Berikut penjabaran makna dari tiap bagian gerakan:
1. Gerakan penghormatan
Bagian awal tarian ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang berjasa dalam penyebaran ajaran Islam.
Gerakan ini juga menjadi simbol permohonan maaf kepada para pemuka adat, mamak, dan ninik yang hadir dalam acara tersebut. Selain itu, penghormatan juga ditujukan kepada kelompok tari lain yang telah atau akan tampil.
2. Gerakan inti nago
Bagian inti terdiri dari beberapa elemen gerak seperti antak siku, bago baranang, dan alang tabang.
Gerakan ini menggambarkan perjuangan seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya, sekaligus mencerminkan semangat para ulama dan pendakwah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam.
Gerakan alang tabang secara khusus melambangkan kebahagiaan dan keceriaan masyarakat.
3. Gerakan penutup
Bagian akhir dari pertunjukan ini berisi gerakan yang menyiratkan permohonan maaf kepada masyarakat Minangkabau. Selain itu, gerakan ini juga menjadi simbol penghormatan terakhir kepada para penonton sebelum pertunjukan selesai.
Pola Lantai Tari Indang
Sebagaimana halnya dengan berbagai tarian tradisional dari daerah lain, pertunjukan ini juga memiliki pola lantai khas yang digunakan untuk membentuk formasi gerak agar tampak lebih bermakna dan estetis.
Secara umum, pola lantai yang digunakan dalam pementasan tarian ini berbentuk horizontal, di mana para penari berbaris sejajar dari sisi kiri ke kanan panggung.
Dalam satu sesi pertunjukan, formasi yang ditampilkan biasanya berupa satu barisan lurus.
Meski demikian, beberapa pementasan juga menggabungkan variasi pola lain seperti bentuk huruf V, V terbalik, pola zig-zag, lingkaran, atau formasi berpasangan dua hingga tiga orang.
Jumlah penari dalam satu pertunjukan tidak memiliki ketentuan baku. Biasanya, jumlahnya berkisar antara lima hingga lebih dari dua puluh lima orang.
Pada masa lampau, tarian ini hanya dibawakan oleh laki-laki karena perempuan tidak diperkenankan tampil di ruang publik.
Namun kini, perempuan juga dapat ikut serta dalam pertunjukan, asalkan tetap menjaga etika berpakaian sesuai norma yang berlaku. Setiap gerakan dalam tarian ini sarat dengan simbol keagamaan.
Misalnya, ketika penari menggerakkan tangan dan menjentikkan jari, gerakan tersebut diyakini sebagai bentuk pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerminkan nilai spiritual yang menjadi inti dari tarian ini.
Busana dan Tata Rias Tari Indang
Pakaian yang dikenakan dalam sebuah pertunjukan tari biasanya mencerminkan asal-usul budaya dari tarian tersebut. Begitu pula dengan kostum yang digunakan dalam pementasan tarian indang, yang merepresentasikan identitas budaya Minangkabau.
Penari perempuan umumnya mengenakan pakaian tradisional khas Minang atau Melayu, dilengkapi dengan berbagai aksesori pendukung.
Busana yang dikenakan terdiri dari atasan longgar, celana hitam yang juga longgar, hiasan kepala, serta sarung khas daerah Minang.
Sementara itu, penari laki-laki mengenakan kostum yang hampir serupa: baju longgar, celana hitam, hiasan kepala, dan sarung khas Minangkabau.
Untuk pelantun syair atau tukang dzikir yang mengiringi pertunjukan, biasanya mengenakan pakaian koko yang tidak memiliki aturan khusus.
Perbedaan utama antara kostum penari laki-laki dan perempuan terletak pada penggunaan penutup kepala atau jilbab oleh penari perempuan.
Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai dakwah yang menjadi dasar dari tarian indang sejak awal kemunculannya.
Warna pakaian yang digunakan dalam pertunjukan ini cukup fleksibel, bisa berupa merah, emas, atau hitam. Sedangkan untuk riasan wajah, tidak ada standar khusus yang harus diikuti oleh penari, baik laki-laki maupun perempuan.
Yang terpenting dari tata rias adalah tampilannya yang enak dilihat. Riasan tidak perlu terlalu mencolok, namun juga tidak terlalu sederhana. Sebaiknya tetap menampilkan ekspresi ceria dan anggun, sesuai dengan karakter tarian yang dibawakan.
Properti Tari Indang
Properti yang digunakan dalam pertunjukan salah satu tarian tradisional Minangkabau ini tergolong sederhana, yaitu alat musik indang.
Alat musik yang juga dikenal dengan nama ripai tersebut dulunya menjadi elemen utama dalam pertunjukan, namun kini sudah jarang digunakan.
Seiring dengan perubahan zaman, tarian ini mengalami sejumlah penyesuaian, termasuk dalam penggunaan alat musik. Saat indang tidak lagi menjadi sumber bunyi utama, lantai panggung mulai dimanfaatkan sebagai alternatif.
Ketika ditepuk oleh penari, lantai panggung mampu menghasilkan suara yang menyerupai bunyi indang, sehingga tetap mendukung irama tarian.
Dulu, beberapa penari juga menggunakan rebana sebagai pelengkap visual dan ritmis dalam pertunjukan. Namun kini, rebana pun mulai ditinggalkan dan digantikan oleh tepukan tangan ke tubuh atau lantai, yang berfungsi serupa dalam menciptakan ritme.
Pada masa lampau, baik indang maupun rebana memiliki peran penting sebagai penentu tempo dalam tarian. Saat ini, jenis alat musik yang digunakan semakin beragam, seperti marwas, perkusi, tamborin, dan bahkan biola.
Untuk mengiringi gerakan tari, beberapa pertunjukan juga memanfaatkan alat musik modern seperti piano dan akordion.
Lagu serta syair yang menjadi bagian dari tarian akan dinyanyikan bersamaan dengan dimulainya pertunjukan, menambah kekayaan nuansa musikal dan makna dari tarian tersebut.
Sebagai penutup, melalui pemahaman sejarah Tari Indang, kita dapat melihat bagaimana seni menjadi jembatan antara tradisi, spiritualitas, dan identitas budaya Minangkabau.